Romantisasi Luka: Ketika Gangguan Mental Dipamerkan dan Dijadikan Identitas di Era Digital

“Di dunia yang lapar perhatian, bahkan penderitaan pun bisa jadi tontonan.”
— Bimo Bakti Pratama, 2025
🧠 Pendahuluan: Dari Kesadaran Menjadi Konsumsi
Dulu, gangguan mental adalah sesuatu yang tersembunyi. Kini, di era sosial media, kita menyaksikan gelombang baru: penderitaan dipamerkan, dijadikan estetik, bahkan digunakan sebagai identitas personal. Fenomena ini bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan bagian dari tren yang dikenal sebagai romantisasi luka—yakni saat trauma, kecemasan, atau diagnosis gangguan mental ditampilkan sebagai sesuatu yang menarik, artistik, atau bahkan “keren”.
Dalam lanskap digital yang digerakkan oleh algoritma dan validasi sosial, gangguan mental tidak lagi hanya dialami—tetapi diproduksi, dikurasi, dan disebarkan untuk dilihat. Sebagian melakukannya sebagai upaya jujur untuk mencari dukungan. Namun sebagian lain—baik sadar atau tidak—terjebak dalam siklus atensi, di mana penderitaan menjadi sarana eksistensi.

📱 1. Media Sosial dan Atensi terhadap Penderitaan
Menurut Ehrenreich & Underwood (2016), remaja yang mengalami kecemasan dan gejala internalisasi lebih cenderung membagikan ekspresi emosional mereka secara publik di media sosial. Dan alih-alih mendapatkan intervensi yang sehat, mereka menerima penguatan sosial dalam bentuk likes, komentar, dan empati cepat saji.
Hal ini juga ditegaskan oleh Phillips (2021) dalam Social Media + Society, bahwa platform digital dirancang untuk memonetisasi emosi. Semakin intens emosi yang ditampilkan, semakin besar potensi viralitasnya. Dalam konteks ini, ekspresi kesedihan dan penderitaan menjadi alat pertunjukan—dan algoritma memberi ruang besar bagi konten semacam itu untuk terus muncul di feed publik.
📍 Lihat juga:
🔗 Layar yang Mengikat: Nomophobia dan Psikologi di Balik Ketergantungan Teknologi
🔗FOMO: Ketika Takut Ketinggalan Menjadi Kekuatan yang Merusak Hidup Anda
🎭 2. Self-Diagnosis dan Persona Luka
Fenomena self-diagnosis online, terutama di TikTok dan Instagram, telah menjadi tren. Remaja kini sering mengidentifikasi dirinya dengan istilah-istilah seperti “aku ADHD banget”, “aku borderline banget”, atau “aku depresi akut”—tanpa diagnosa klinis yang valid. Penelitian oleh Giles (2022) menyebut ini sebagai bentuk performative identity, yakni saat gangguan mental menjadi bagian dari citra diri digital.
Alih-alih berfokus pada pemulihan, banyak dari mereka membentuk persona berdasarkan luka, seolah penderitaan adalah satu-satunya cara agar mereka terlihat “menarik”, “relatable”, atau “autentik”. Pada titik ini, penderitaan bukan lagi sesuatu yang ingin disembuhkan—melainkan sesuatu yang harus dipelihara untuk tetap relevan.
📍 Relevan dengan fenomena:
🔗 Self-Serving Bias: Ketika Kita Terlalu Percaya Bahwa Kita Selalu Benar
🔗Membedah Buku “The Anxious Generation”: Psikologi di Balik Kecemasan Generasi Muda
🔄 3. Komunitas Online: Dukungan atau Jebakan?
Komunitas dengan tagar #mentalhealthawareness memang dibangun untuk saling mendukung. Namun, riset oleh Chancellor et al. (2016) menunjukkan bahwa komunitas online dengan tema gangguan mental bisa menjadi tempat normalisasi perilaku berbahaya, seperti dalam kasus komunitas pro-eating disorder. Di sana, gangguan tidak dianggap sebagai penyakit, tapi gaya hidup estetik—yang dijaga, dibanggakan, dan diidolakan.
Fenomena serupa kini terjadi di komunitas-komunitas “sad aesthetic” atau “sad girl/boy culture” yang menyamakan kesedihan dengan kedalaman, dan menciptakan budaya di mana semakin hancur seseorang terlihat, semakin ‘autentik’ ia dianggap.
🔗 Echo Chamber: Ketika Kita Terjebak dalam Gelembung Pikiran Sendiri
🧩 4. Dampak Psikologis: Identitas yang Dibangun dari Luka
Dampak dari romantisasi gangguan mental tidak bisa diremehkan:
- 🧠 Overidentifikasi: Individu merasa bahwa dirinya “adalah gangguannya.” Mereka takut kehilangan perhatian jika sembuh.
- 🕳️ Keterikatan terhadap penderitaan: Luka menjadi cara untuk mendapat validasi dan penerimaan.
- ⛓️ Terjebak dalam kekosongan eksistensial: Ketika satu-satunya hal yang membuat seseorang merasa “ada” adalah penderitaan, maka kesembuhan justru dianggap kehilangan jati diri.
Ini menciptakan risiko yang besar, terutama pada remaja yang sedang membentuk identitas. Tanpa disadari, mereka sedang menyulam luka menjadi label permanen yang menempel di kepala dan hati mereka.
📍 Pelajari lebih lanjut:
🔗 Perfeksionisme yang Tumbuh dari Kenyamanan: Luka Tak Terlihat Anak yang Dimanjakan
🔗Dunia yang Diciptakan oleh Algoritma: AI dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Keputusan Psikologis Manusiaegadang Jadi Bentuk Pelarian
💡 Apa yang Bisa Kita Lakukan?
- Bedakan antara edukasi dan eksibisi. Tidak semua konten mental health di media sosial bersifat edukatif. Kita perlu lebih kritis terhadap konten yang sekadar menjual emosi.
- Dorong refleksi, bukan glorifikasi. Ajarkan bahwa luka bisa jadi sumber kekuatan, tapi bukan satu-satunya sumber identitas.
- Kembalikan makna pulih. Kesembuhan bukan pengkhianatan terhadap komunitas atau identitas, tapi bentuk keberanian dan pertumbuhan.
🧭 Kesimpulan: Luka Bukan Label
Kesadaran akan gangguan mental adalah hal yang baik—tapi menjadikannya simbol estetik atau konten viral adalah bentuk pengaburan makna. Gangguan mental bukan tren, bukan aksesori, dan bukan jati diri. Mereka adalah bagian dari perjuangan manusia yang harus dihormati—dan dihadapi dengan kejujuran, bukan dibungkus glitter di layar ponsel.
“Jika luka kita dijadikan panggung, lalu kapan kita belajar untuk menyembuhkan?”
— Bahaspsikologi.com, 2025
Luka yang kita alami seringkali bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kesadaran. Pola penyembuhan ini dijelaskan dengan kuat melalui struktur Hero’s Journey dalam psikologi manusia.
Jika kamu pernah merasa beban masa lalu masih menahan langkahmu hari ini, kamu bisa membaca artikel Memaafkan Masa Kecil yang Tak Meminta Maaf, tentang bagaimana menyentuh kembali luka itu dengan kehadiran dan kasih sayang.
baca juga :
Saat kita sulit merasa tenang dan terus terjebak di dalam kepala sendiri, mungkin itu bukan karena kita terlalu pintar—tapi karena ada bagian dari diri kita yang sedang meminta disembuhkan. Baca refleksinya di Overthinking Bukan Ciri Orang Cerdas, Tapi Luka yang Belum Disembuhkan.
Referensi
Ehrenreich, S. E., & Underwood, M. K. (2016).
Adolescents’ internalizing symptoms as predictors of the content of their Facebook communication and responses received from peers.
Journal of Research on Adolescence, 26(3), 568–582.
https://doi.org/10.1111/jora.12215
Chancellor, S., Pater, J. A., Clear, T., Gilbert, E., & De Choudhury, M. (2016).
#thyghgapp: Instagram content moderation and lexical variation in pro-eating disorder communities.
Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing.
https://doi.org/10.1145/2818048.2819963
Giles, D. C. (2022).
“Self-diagnosis” and identity on TikTok: The performative side of mental health awareness.
Media, Culture & Society, 44(6), 1014–1030.
https://doi.org/10.1177/01634437221083095
Phillips, W. (2021).
The Internet of Feelings: The soft side of hard platforms.
Social Media + Society.
https://doi.org/10.1177/20563051211028207
BBC Future. (2023, May 22).
Is it helpful or harmful to romanticise mental illness online?
Retrieved from https://www.bbc.com/future/article/20230522-is-it-helpful-or-harmful-to-romanticise-mental-illness-online


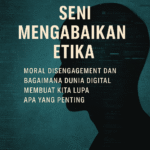





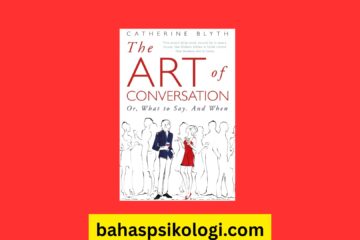


0 Comments